 Septria Margi
Septria Margi
Sejarah | 2025-11-10 22:23:36
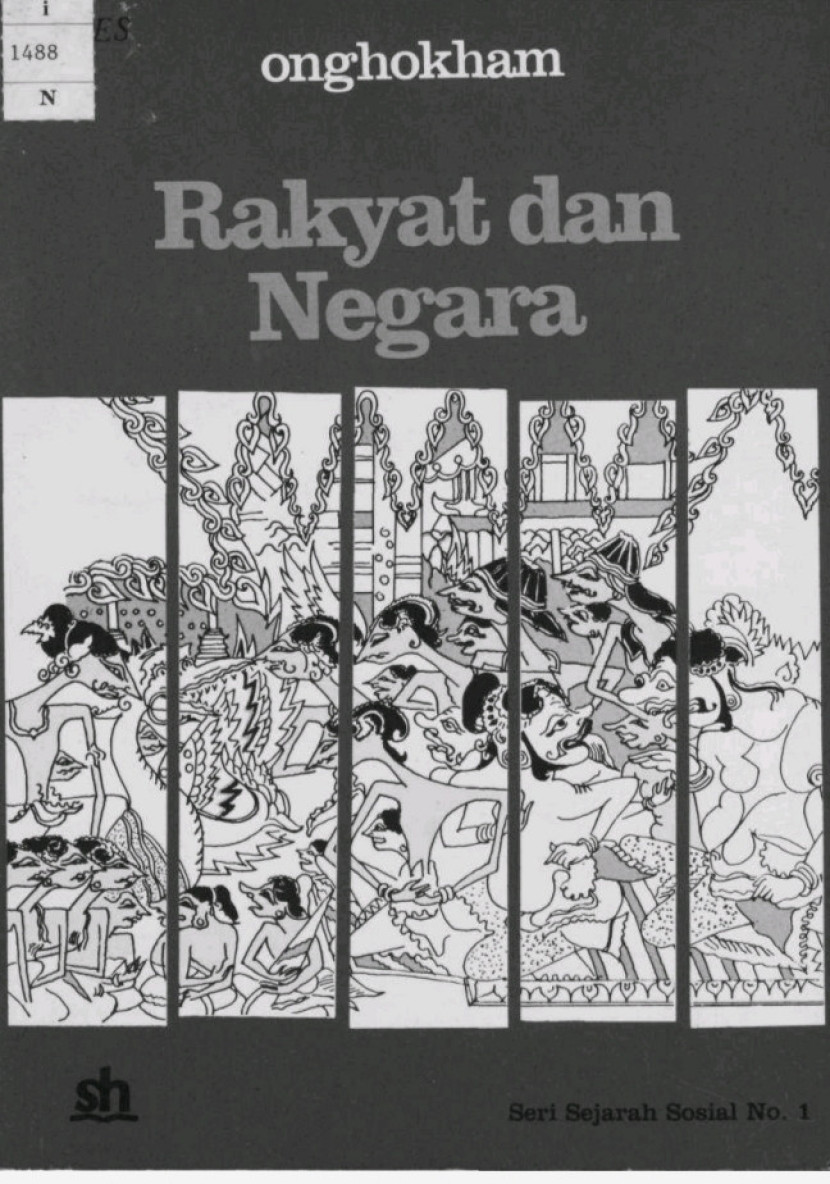
I. Sukarno: Mitos dan Realitas – Pemimpin yang Tak Terduga
Sukarno, sang Proklamator, sering digambarkan sebagai mitos hidup. Onghokham mengungkap kompleksitasnya melalui analisis biografis yang mendalam, menunjukkan bagaimana kepribadian Gemini-nya mencerminkan dualitas Indonesia: antara tradisi dan modernitas, rakyat dan elite. Latar Belakang Keluarga dan Pendidikan: Lahir dari priyayi rendahan, Sukarno naik ke elite melalui pendidikan HBS dan THS. Ini menempatkannya di antara hanya 78 orang Indonesia berpendidikan tinggi pada 1927, membuatnya unik di tengah pergerakan nasional. Ideologi Muda: Tulisan-tulisan awalnya anti-imperialisme dan pro-Islam, tetapi ia berkembang menjadi nasionalis yang mengintegrasikan Marxisme. Konsep "Marhaenisme" – rakyat kecil seperti petani miskin – menjadi fondasi populismenya. Strategi Revolusioner: Sukarno membangun "negara dalam negara" melalui PNI dan PPPKI, menggunakan pidato-pidato berapi-api untuk menggelorakan massa. Penangkapannya pada 1930 hanya memperkuat karismanya.
Perpecahan dengan Rekan: Konflik dengan Hatta dan Sjahrir menunjukkan perbedaan: Sukarno fokus pada semangat massa, sementara yang lain pada kader dan ekonomi. Ini mencerminkan dilema pergerakan: antara revolusi emosional dan pembangunan rasional. Peran dalam Revolusi: Sukarno sebagai simbol kemerdekaan, tetapi ia kurang terlibat dalam strategi militer. Diplomasinya dengan Jepang dan Belanda menunjukkan pragmatisme, namun ia sering terisolasi dari realitas lapangan. Era Kemerdekaan: Sebagai presiden, Sukarno mendorong Demokrasi Terpimpin untuk mengatasi krisis, tetapi ini berakhir dengan jatuhnya ia pada 1966. Onghokham melihatnya sebagai pemimpin masa krisis, yang bangkit saat bangsa butuh kesatuan. Analisis Menarik: Sukarno bukan "Ratu Adil" seperti mitos Jawa, melainkan produk kolonialisme. Ia berdiri sendiri, tanpa sekutu kuat, mencerminkan kesepian pemimpin revolusioner. Dalam konteks modern, ia mengingatkan kita pada bahaya karisma yang tak terkendali.
2. Refleksi Seorang Peranakan Mengenai Sejarah Cina-Jawa – Identitas Ganda di Tengah Kolonialisme
Onghokham, sebagai peranakan Cina-Jawa, memberikan pandangan pribadi yang kaya akan emosi. Ia menguraikan evolusi masyarakat Cina-Jawa dari minoritas asing menjadi bagian integral Indonesia, dipengaruhi oleh kolonialisme Belanda. Asal-Usul dan Konsolidasi: Orang Cina datang sejak abad ke-17, tetapi konsolidasi terjadi pada abad ke-18 dengan perkawinan campuran. Istilah "peranakan" mula-mula untuk Cina Muslim, kemudian untuk keturunan setempat, berbeda dari "singkeh" pendatang baru.
 Photographs of Peranakan Chinese-Indonesia Families in Dutch-East Indies
Photographs of Peranakan Chinese-Indonesia Families in Dutch-East Indies
Peran dalam Ekonomi Kolonial: Orang Cina menjadi perantara ekonomi, menguasai monopoli seperti candu dan rumah gadai. Ini menciptakan elite kapitalis, tetapi juga ketegangan dengan petani Jawa. Pembatasan dan Diskriminasi: Sistem pecinan dan pas-jalan membatasi gerak mereka, tetapi Belanda membutuhkannya untuk eksploitasi ekonomi. Ini menciptakan dilema: Cina sebagai "musuh yang diperlukan". Perubahan Abad ke-20: Krisis ekonomi mendorong pergerakan nasionalis Cina, tetapi mereka terasing dari revolusi Indonesia. Modernisasi hukum keluarga (1917) mengubah struktur keluarga dari besar menjadi inti. Refleksi Pribadi: Onghokham menyoroti identitas ganda: antara Cina dan Jawa. Ia mengkritik pandangan Barat yang melihat Cina-Jawa sebagai "asing", padahal mereka telah berasimilasi. Ini relevan dengan isu etnis di Indonesia saat ini, seperti diskriminasi terhadap Tionghoa. Analisis Menarik: Sejarah Cina-Jawa mencerminkan tema universal imigrasi: dari marginalisasi ke integrasi. Onghokham menunjukkan bagaimana kolonialisme membentuk identitas etnis, dan tantangan bagi Indonesia untuk membangun kesatuan tanpa diskriminasi.
3. Penelitian Sumber-Sumber Gerakan Mesianis – Takhyul atau Resistensi Sosial?
Gerakan mesianis, seperti pemberontakan Patik 1885, sering dianggap sebagai fanatisme takhyul. Onghokham membuktikan sebaliknya: ini respons rasional terhadap eksploitasi kolonial, dengan akar dalam struktur sosial Jawa. Kasus Patik: Pemberontakan dipicu pajak tanah tinggi (16% dari penghasilan), bukan mitos Ratu Adil. Belanda salah paham, melihatnya sebagai ancaman primordial. Konsep Kawula-Gusti: Raja sebagai Dewa-Raja, dengan oposisi dari tokoh seperti Raden Kajoran. Ramalan umur kerajaan mencerminkan ketidakstabilan dinasti. Tanah dan Pajak: Sistem feodal membuat petani miskin, dengan proses "pancasan" (pengurangan milik). Pajak tinggi dan kerja paksa kolonial memperburuk. Perantara Kekuasaan: Palang dan weri sebagai calo, menimbulkan korupsi dan ketidakpuasan. Ini menciptakan "gerakan bawah tanah" yang meledak dalam pemberontakan. Pakem Jayabaya: Serat ini menggambarkan zaman edan (kemiskinan, pajak tinggi) versus zaman emas (keadilan). Ini bukan eskatologi murni, melainkan kritik sosial. Analisis Menarik: Gerakan mesianis sebagai bentuk resistensi petani terhadap kolonialisme. Onghokham menunjukkan bagaimana mitos digunakan untuk menyembunyikan isu ekonomi, relevan dengan gerakan sosial modern seperti petani di era reformasi.
4. Sejarah Pembesar di Indonesia – Dari Feodalisme ke Birokrasi Modern
Onghokham membandingkan aparatur negara tradisional (priyayi di Jawa, orang-kaya di Aceh) dengan birokrasi modern. Ia menunjukkan kelemahan struktur feodal yang bergantung pada hubungan pribadi, bukan hukum. Hubungan Pribadi: Aparatur tradisional didasarkan loyalitas pribadi, bukan aturan obyektif. Ini membuat negara lemah dan rentan korupsi. Priyayi Jawa: Sebagai elite militer dan birokrat, mereka menguasai tanah dan tenaga kerja. Otonomi keuangan menciptakan pungutan liar.Orang-Kaya Aceh: Hulubalang sebagai pedagang dan pemimpin perang, dengan kekuasaan otonom. Konflik dengan sultan sering berakhir dengan kudeta. Kelemahan Struktur: Aparatur lemah, mengandalkan teror dan mata-mata. Ideologi dan agama digunakan untuk legitimasi, tetapi sering menimbulkan oposisi. Analisis Menarik: Perbandingan ini menunjukkan evolusi dari feodalisme ke negara modern. Di Indonesia, transisi ini belum selesai, dengan sisa-sisa feodalisme masih terlihat dalam birokrasi kita. Onghokham mengingatkan bahaya korupsi dan nepotisme.
5. Kedudukan Politik Kaum Militer dalam Sejarah – Kekuatan yang Tak Terkendali
Militer sebagai "pemilik kekuatan" sering menjadi ancaman bagi demokrasi. Onghokham menganalisis peran militer dari zaman feodal hingga modern, menunjukkan risiko "senjata makan tuan". Militer sebagai Penakluk: Elite militer menguasai harta dan tenaga rakyat, dengan hak atas jarahan perang. Ini menciptakan struktur feodal. Hak dan Milik: Kekayaan militer tidak stabil; sering disita oleh raja atau bangsawan lain. Rakyat hanya memiliki hak pakai. Masyarakat Militer: Militer konservatif, dengan latihan untuk ketaatan. Ini berbeda dari kaum cerdik-pandai yang inovatif. Militerisme Modern: Di abad ke-20, militer profesional, tetapi risiko praetorianisme (klik militer berkuasa). Contoh: kudeta di Amerika Latin. Analisis Menarik: Onghokham menyoroti dilema: militer diperlukan untuk keamanan, tetapi bisa menjadi tiran. Di Indonesia, peran ABRI pasca-1965 mencerminkan ini, dengan tantangan demokratisasi saat ini.
6. Angkatan Muda dalam Sejarah dan Politik – Motor Perubahan atau Kekuatan Destruktif?
Pemuda sering diidealiskan sebagai agen perubahan. Onghokham menguraikan peran angkatan muda dari revolusi hingga modern, dengan fokus pada generasi intelektual. Peran Historis: Pemuda aktif dalam perang dan revolusi, dengan semangat dan tenaga fisik. Contoh: pemuda 1928 dan proklamasi 1945. Angkatan Muda Indonesia: Generasi muda sebagai motor nasionalisme, tetapi sering terpecah antara idealisme dan pragmatisme. Tantangan Modern: Pemuda intelektual menghadapi isu-isu seperti korupsi dan ketimpangan sosial, sering melalui demonstrasi. Analisis Menarik: Onghokham melihat pemuda sebagai potensi besar, tetapi juga risiko radikalisme. Di era digital, demonstrasi mahasiswa seperti 1998 menunjukkan kekuatan mereka untuk perubahan.
7. Pemberontakan Madiun 1948: Drama Manusia dalam Revolusi – Konflik Ideologi di Tengah Perang
Pemberontakan Madiun oleh PKI dipimpin Muso adalah tragedi revolusi. Onghokham menggambarkannya sebagai drama manusia, bukan sekadar konflik politik. Latar Belakang: Di tengah perang kemerdekaan, PKI mencoba kudeta untuk mendirikan republik sosialis. Muso sebagai pemimpin karismatis.
 Pemberontakan PKI Tahun 1948 di Madiun
Pemberontakan PKI Tahun 1948 di Madiun
Perkembangan: Pemberontakan gagal karena kurang dukungan massa dan intervensi tentara nasionalis. Ribuan tewas. Dampak: Memperkuat posisi Sukarno-Hatta, tetapi meninggalkan trauma bagi PKI. Analisis Menarik: Ini mencerminkan dilema revolusi: antara nasionalisme dan ideologi asing. Onghokham menyoroti manusia di balik peristiwa, relevan dengan konflik politik saat ini.
8. Proses Kesenian Indonesia dari Masa ke Masa – Ekspresi Budaya dalam Perubahan Sosial
Kesenian sebagai cermin masyarakat. Onghokham menguraikan evolusi kesenian Indonesia dari tradisional hingga modern. Evolusi: Dari wayang dan gamelan tradisional, dipengaruhi Hindu-Budha, Islam, dan kolonialisme. Peran Sosial: Kesenian sebagai identitas nasional, tetapi juga alat propaganda (misalnya, dalam revolusi). Modernisasi: Pasca-kemerdekaan, kesenian berinovasi, tetapi menghadapi komersialisasi. Analisis Menarik: Onghokham melihat kesenian sebagai sarana resistensi budaya. Di era globalisasi, ini menantang pelestarian identitas Indonesia.
Sumber : Onghokham (1983). Rakyat dan Negara. Jakarta: Sinar Harapan
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.

 2 hours ago
2
2 hours ago
2















































