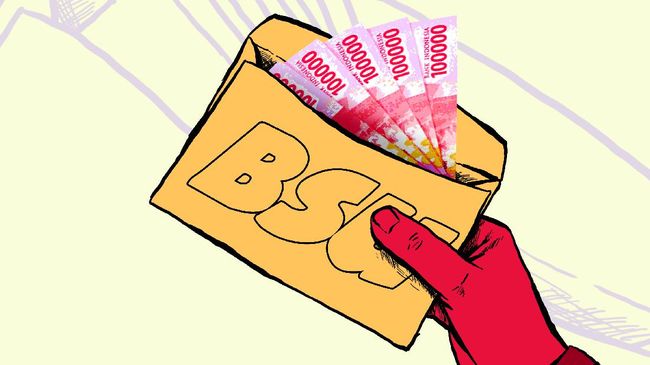Oleh : Dr Devie Rahmawati, Assoc Prof Vokasi UI
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Beberapa hari ini, Masjid Istiqlal menjadi saksi sebuah peristiwa budaya yang sarat makna: Pameran Dialog Peradaban Gus Dur dan Daisaku Ikeda. Pameran ini menampilkan persahabatan dua tokoh besar yang berbeda bangsa, agama, dan latar belakang, namun bersatu dalam satu keyakinan: dialog sebagai nafas peradaban.
Apa yang lebih berbahaya dari polarisasi politik atau konflik bersenjata? Jawabannya mungkin ada di genggaman kita: hilangnya seni berdialog. Media sosial menjadikan kita cepat marah, gampang bereaksi, tetapi miskin mendengar. Ironisnya, di tengah krisis komunikasi global ini, kita pernah punya teladan: Gus Dur dan Daisaku Ikeda, dua tokoh yang mengajarkan bahwa hanya dengan dialog, peradaban bisa bertahan.
Generasi Z dan Paradoks Konektivitas
Generasi Z sering dipuji sebagai generasi paling melek teknologi. Mereka lahir bersamaan dengan internet, tumbuh bersama media sosial, dan kini fasih menguasai bahasa visual global : dari meme, emoji, hingga video singkat. Namun, survei Boundless (2024) menemukan fakta kontras: banyak di antara mereka justru pesimis, sinis, dan apatis. Mereka melihat dunia terlalu rusak untuk diperbaiki, dari krisis iklim hingga ketidaksetaraan sosial. Generasi paling terkoneksi ini justru berisiko menjadi generasi paling rapuh.
Riset 2024 mengungkap pola komunikasi Gen Z yang makin singkat, terfragmentasi, dan dangkal. Emoji dan sticker menggantikan kata-kata panjang. Percakapan serius bergeser menjadi kecepatan reaksi di layar gawai. Efisiensi ini memang memudahkan interaksi, tetapi mengikis keterampilan dasar: kesabaran, mendengarkan, dan membangun pemahaman bersama.
Fenomena ini sejalan dengan penelitian Eropa (2021) yang menyebut media sosial cenderung membuat kita lebih cepat marah. Emosi negatif, khususnya kemarahan, terbukti menyebar lebih cepat daripada informasi netral atau positif.
Inilah mengapa, di ruang digital, Gen Z tampak lantang. Namun data kesehatan publik justru menyingkap sisi lain. Laporan BMC Public Health (2025) menunjukkan peningkatan signifikan kecemasan, depresi, dan rasa kesepian di kalangan anak muda. Kajian pastoral bahkan menyebut mereka “haus akan kedamaian mendalam” (longing for deep peace).
Fenomena fear of missing out (FoMO) menambah kerentanan. Studi terbaru menunjukkan dorongan untuk selalu tampil di media sosial, selfie, unggahan, ekspos diri, membuat anak muda semakin rapuh secara emosional. Mereka tampak kuat di luar, tetapi kosong di dalam.
Kondisi ini diibaratkan lampu yang terang di luar, tetapi minyaknya hampir habis di dalam. Cahaya luar bisa menipu, namun batin yang rapuh mudah padam. Inilah generasi yang butuh bukan hanya teknologi baru, tetapi juga dialog batin dan ruang percakapan yang menyehatkan jiwa.
Dialog: Infrastruktur Sosial yang Hilang
Dialog bukan sekadar sopan santun atau pertukaran kata. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa dialog memiliki kekuatan unik untuk membentuk cara berpikir, memperdalam pemahaman, dan menumbuhkan empati.
Riset pendidikan (2020) menegaskan bahwa pembelajaran berbasis dialog lebih efektif dibanding metode monolog atau ceramah. Ketika seseorang terlibat dalam percakapan timbal balik, mereka tidak hanya menyerap informasi, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis, merefleksikan nilai-nilai, dan membangun kesadaran kolektif. Dengan kata lain, dialog melatih otak sekaligus hati.
Temuan ini sejalan dengan laporan American Psychological Association (2023) bahwa percakapan bermakna terbukti meningkatkan kesehatan mental, mengurangi rasa kesepian, dan memperkuat kesejahteraan sosial. Mind & Life Institute (2023) juga menambahkan, dialog adalah salah satu mekanisme paling efektif untuk menurunkan polarisasi dan membuka ruang penyelesaian konflik lintas budaya.
Sayangnya, keterampilan ini justru paling terkikis di era digital. Generasi muda semakin terlatih bereaksi cepat, tetapi kehilangan kesabaran untuk mendengar. Mereka ahli posting, tetapi miskin pausing. Padahal, tantangan besar dunia, dari konflik siber, krisis iklim, hingga ketidakadilan sosial, tidak bisa dijawab dengan monolog dan kemarahan, melainkan dengan keberanian untuk duduk bersama, bernegosiasi, dan mencari jalan tengah.
Daisaku Ikeda pernah berpesan bahwa dialog bukanlah sekadar tawar-menawar antara pihak yang berlawanan, melainkan pertemuan hati yang mampu membangkitkan sisi terbaik dari setiap orang. Karena itu, dialog sejati bukan hanya cara berkomunikasi, tetapi fondasi yang menjaga peradaban tetap hidup dan manusia tetap terhubung dengan tulus.
Praktik Baik Dunia
Banyak inisiatif global telah membuktikan bahwa dialog bisa diajarkan, diukur, dan ditumbuhkan:
UC Berkeley – Bridging Differences Course: melatih empati dan keterampilan dialog berbasis riset ilmiah.
Stanford Dialogue Labs: percakapan lintas ideologi yang terbukti menurunkan polarisasi mahasiswa.
Lost Art Labs (Eropa–AS): menghidupkan kembali percakapan tatap muka sebagai keterampilan sipil.
Scandinavia’s Digital Compassion Design: fitur pause untuk mencegah komentar impulsif.
Semua ini menegaskan: dialog bukan romantisme masa lalu, melainkan kebutuhan psikososial paling nyata di abad ini.
Rekomendasi untuk Indonesia dan Asia Tenggara
Infrastruktur Dialog. Pemerintah tidak cukup membangun broadband, tetapi juga dialog-band: pusat riset percakapan lintas budaya, laboratorium dialog, hingga pelatihan fasilitator.
Pertukaran Pemuda Lintas Negara. ASEAN perlu mendorong pertukaran pemuda yang berbasis praktik dialog, bukan sekadar pertukaran budaya formal.
Insentif Platform Pro-Dialog. Mendesak platform digital untuk memberi sorotan pada konten yang sehat dan bernas, bukan hanya konten yang memancing emosi.
Kolaborasi Universitas dan NGO. Kampus wajib memasukkan dialog ke dalam kurikulum, sementara masyarakat sipil menghadirkannya di akar rumput.
Indonesia punya warisan kaya: musyawarah, gotong royong, rembug desa. Lebih dari itu, kita punya tokoh teladan seperti Gus Dur, yang bersama Ikeda Sensei meneguhkan bahwa dialog adalah jalan melampaui perbedaan.
Penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa Universitas Indonesia kepada Daisaku Ikeda pada 2009 adalah simbol pengakuan akan nilai dialog lintas bangsa dan agama. Kini, warisan itu perlu kita lanjutkan, dengan menjadikan Indonesia pemimpin gerakan global dialog.
Dengan menggabungkan kearifan lokal dan praktik global, kita bisa mengubah Generasi Z dari pessimistic natives menjadi optimistic builders: bukan hanya generasi yang reaktif, tetapi generasi yang kolaboratif, resilien, dan penuh harapan.
Jika peradaban dahulu dibangun oleh dialog, maka kerapuhannya hari ini lahir dari hilangnya dialog. Generasi Z tidak boleh dibiarkan tumbuh hanya fasih dalam meme tetapi bisu dalam makna; ahli melampiaskan amarah tetapi miskin empati.
Dialog adalah infrastruktur sosial yang hilang, dan justru menjadi inovasi paling mendesak abad ini. Tanpanya, kita akan mencetak generasi rapuh. Dengannya, kita bisa melahirkan generasi global yang siap membangun jembatan, bukan tembok.

 3 hours ago
2
3 hours ago
2