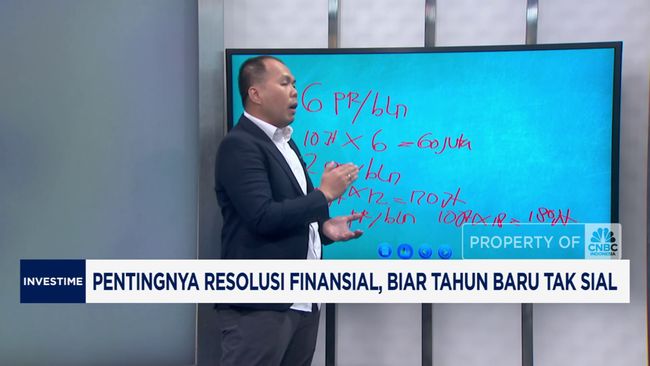Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah harus belajar dari India, yang kerap dikenal sebagai salah satu negara yang menggelar program pengampunan pajak atau tax amnesty berulang kali, namun gagal menaikkan kepatuhan pajak di negaranya.
Ini karena wacana bergulirnya program tax amnesty jilid III muncul, setelah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.
Pakar pajak yang merupakan Co-Founder Botax Consulting Indonesia Raden Agus Suparman mengatakan, selain Indonesia, negara yang kerap menggelar program tax amnesty salah satunya adalah India. India diketahui rutin menggelar tax amnesty pada 1952, 1965, 1975, 1981, 1985, 1986, 1991, dan terakhir pada 1997.
"Ada dan contoh yang paling terkenal adalah negara India. Tax Amnesty di India pada tahun 1970 sampai dengan 1980-an menjadi bahan kajian para ahli," kata Raden kepada CNBC Indonesia, Kamis (21/11/2024).
Raden mengatakan, tax amnesty di India yang berulang sebetulnya terbilang tidak berhasil. Karena membuat sentimen di tengah masyarakatnya bahwa pemerintah ke depannya akan terus menggelar program pengampunan pajak, sehingga tingkat kepatuhannya terkikis.
Rasio pajak terhadap PDB atau tax to gdp ratio di India pun hanya sedikit di atas Indonesia, yakni kisaran 11%, sedangkan Indonesia secara stagnan hanya bergerak di kisaran 10%. Padahal, program tax amnesty jilid I telah digelar pada 2016, dan tax amnesty jilid II pada 2022 dengan nama program pengungkapan sukarela (PPS).
"Dan hasilnya memang, tax amnesty yang berulang, apalagi jangka waktunya sangat dekat seperti di India, justru hasilnya tidak baik. Wajib Pajak tidak menganggap spesial lagi tax amnesty tersebut. Karena menurut mereka, tahun depan juga ada lagi. Begitu seterusnya sehingga tidak ada momentum 'kesempatan langka!'," ucap Raden.
Oleh sebab itu, Raden menganggap, pemerintah tak perlu menggelar tax amnesty jilid 3, kecuali memang ada permintaan dari pengusaha super kaya atau crazy rich yang akan memasukkan uangnya (repatriasi) dari Luar Negeri ke Dalam Negeri.
"Tax amnesty jilid 3 tidak diperlukan karena berdasarkan pengalaman tax amnesty jilid I tujuan awal Presiden Jokowi menarik dana Rp11.000 triliun dari Luar Negeri tidak tercapai. Hasil repatriasi yang dilaporkan pada tax amnesty jilid I hanya Rp146 triliun. Itu pun baru pelaporan yang bersedia dengan menebus sesuai tarif waktu itu. Wajib Pajak diberikan waktu paling lama 3 tahun setelanya untuk melakukan realisasi," ucapnya.
Lagi pula, ia menekankan, Ditjen Pajak sebagai otoritas pajak di Indonesia tidak pernah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap wajib pajak yang mengikuti program tax amnesty, apakah betul-betul melakukan repatriasi atau tidak.
"Berdasarkan pengalaman saya sebagai kepala seksi pengawasan waktu itu, Ditjen Pajak tidak pernah melakukan pengawasan dan melakukan evaluasi Wajib Pajak mana yang benar-benar melakukan repatriasi, dan Wajib Pajak mana yang tidak melakukan. Sehingga, bisa jadi dana repatriasi Rp146 triliun tersebut tidak benar-benar masuk semua ke Indonesia," ucapnya.
Jika tax amnesty jilid 3 tetap akan dijalankan, ia menyarankan supaya pemerintah fokus saja ke pengampunan pajak untuk dana repatriasi. Selain itu, prosedur repatriasi harus diperketat, yaitu ditampung dulu di Bank Indonesia selama 6 bulan, selanjutnya bisa diambil tetapi tetap diinvestasikan di Dalam Negeri.
"Kemudian Bank Indonesia melaporkan siapa saja yang telah merealisasikan penyimpanan di Bank Indonesia. Jika ada Wajib Pajak yang tidak merealisasikan penyimpanan, tapi memanfaatkan tax amnesty, maka tambah sanksi 200% seperti sanksi administrasi di tax amnesty jilid I," tegasnya.
Meski begitu, ia menekankan, program amnesti pajak tidak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Raden mendasari pada beberapa kajian-kajian akademis, yang menyodorkan hasil tax amnesty jilid I tidak meningkatkan kepatuhan pajak.
"Sehingga asumsi bahwa pengampunan pajak akan meningkatkan kepatuhan tidak terbukti. Hasil penelitian yang sama terjadi juga di India dan Amerika Serikat bahwa tax amnesty tidak meningkatkan kepatuhan pajak," ucap Raden.
Alasannya utama hasil dari penelitian yang mengungkapkan amnesti pajak tidak membuat kepatuhan meningkat karena tax amnesty ditujukan untuk para Wajib Pajak yang tidak patuh, sehingga wajib pajak itu hanya patuh saat ada tax amnesty saja.
"Setelah itu, mereka kembali kepada kebiasaannya sebagai Wajib Pajak tidak patuh. Tidak ada niatan untuk patuh sejak awal," ucapnya.
Di sisi lain, program tax amnesty ia katakan juga tidak meningkatkan basis pajak, meskipun harta yang dilaporkan di SPT Wajib Pajak tentu meningkat, dan dengan dilaporkannya harta-harta tersebut, diharapkan pajaknya juga meningkat.
Tapi, menurut Raden, kenyataannya Wajib Pajak hanya sekedar lapor harta, dan tidak ada peningkatan pajak yang dibayarkan. Walaupun Wajib Pajak mengakui memiliki properti di banyak di Luar Negeri, tetapi pengakuan mereka selalu bahwa properti tersebut digunakan keluarganya, tidak disewakan, dan jarang yang melaporkan dijual walaupun mungkin saja sudah dijual.
"Ditjen Pajak sudah melakukan pengawasan atas harta-harta tax amnesty jilid I yang dilaporkan di SPT Tahunan. Menanyakan penggunaannya. Dan jawabannya sangat jarang yang mengakui adanya harta yang disewakan di Luar Negeri. Atau harta tersebut menghasilkan objek pajak baru. Ditjen Pajak pun tidak ada data yang dapat melakukan verifikasi atas pengakuan Wajib Pajak tersebut," paparnya.
Sementara itu, Pakar Pajak yang merupakan Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono juga mengingatkan, penerimaan pajak yang meningkat saat adanya program tax amnesty tidak diikuti di tahun-tahun berikutnya setelah TA berakhir.
Sebab, perilaku tax evasion dan/atau tax avoidance akan tetap selalu ada karena karakteristik pajak itu seperti perampokan yang memaksa. Hal ini kata dia ditegaskan juga oleh Pasal 23A UUD 1945: Pajak dan pungutan yg bersifat memaksa untuk keperluan negara didasarkan UU.
Selain itu, Prianto mengingatkan, ada falsafah pajak yang menyebutkan taxation without representation is robbery atau pajak tanpa perwakilan adalah perampokan. Maka, kebijakan pajak (termasuk TA) membutuhkan persetujuan wakil rakyat di DPR. Bentuknya adalah UU. Bila sudah ada undang-undangnya, pajak tidak lagi sama dengan perampokan, meski karakteristik "memaksa" masih tetap ada.
Ia pun menganggap, fakta bahwa TA akan terus berulang memunculkan rasa ketidakadilan. Masalahnya adalah pengemplang pajak (tax evader) mendapatkan karpet merah untuk membayar pajak dengan tarif khusus. Tarif khusus tersebut lebih rendah dari tarif normal di UU Pajak.
Sementara itu, wajib pajak yang sudah patuh harus membayar pajak sesuai tarif normal. "Kondisi demikian dapat memunculkan antipati bagi Wajib Pajak patuh dengan mengatakan, "Kalau begitu, saya tidak perlu patuh karena nantinya juga akan ada TA jilid berikutnya". Pernyataan demikian sangat beralasan karena ada perlakuan tidak adil dari pemerintah ketika ada kebijakan TA," ucap Prianto.
(arj/mij)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Tax Amnesty Ada Lagi, Pesanan Siapa?
Next Article Belum Lama Pengemplang Pajak Diampuni, Kenapa 2025 Dapat Lagi?

 3 months ago
35
3 months ago
35